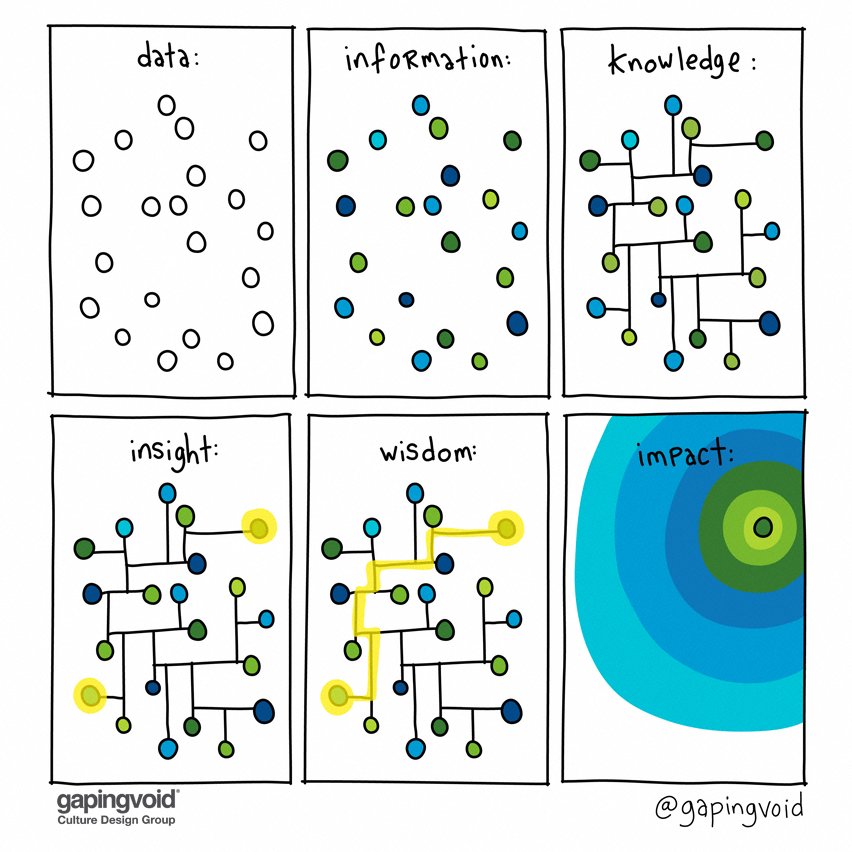Junghuhn pertama tiba di Jawa pada bulan Oktober tahun 1835. Bulan-bulan pertamanya dihabiskan di Weltevreden (kini Menteng) sebagai petugas kesehatan di rumah sakit pemerintah kolonial. Di waktu-waktu itu dia tidak banyak berjalan-jalan, hanya ke sekitar Weltevreden dan Batavia. Pertama kali Junghuhn benar-benar bepergian untuk berwisata adalah pada bulan Mei tahun 1836, ketika ia dipindahtugaskan ke Jogja.
Cerita ini adalah kisah Junghuhn berpetualangang ke Gunung Kidul, tepatnya ke Gua Rongkop. Ceritanya ditulis oleh Wormser pada buku Frans Junghuhn (1840), yang berbahasa Belanda. Cerita ini saya terjemahkan bebas dengan sedikit modifikasi. Saya menggunakan kata ganti orang pertama untuk merujuk Junghuhn. Sebelumnya Wormser menggunakan kata ganti orang ketiga.
Cerita ini menarik karena Junghuhn membuat lukisan Gua Rongkop yang dimuat dalam Elf Landschaft- Ansichten von Java (1853). Selain Gua Rongkop, Junghuhn juga melukis Gunung Sewu dan Gunung Gamping dan masih banyak lukisan lainnya dalam periode waktunya di Jogja. Gambarnya digunakan sebagai feature image dari artikel ini. Untuk memperjelas deskripsi teks, disarankan sambil melihat lukisannya.
Berikut ceritanya:
Aku bertugas di Jogja sebagai petugas kesehatan kelas mulai dari 3 Maret 1836 hingga Oktober 1836, tidak lama, hanya 7 bulan saja. Dua bulan pertama itu sangat sibuk, sehingga aku tidak bisa banyak menjelajah. Baru setelah dua bulan aku mengambil cuti seminggu untuk pergi ke Pegunungan Selatan. Sepulang dari Pegunungan Selatan aku dipaksa untuk terus bekerja lagi selama 3 bulan, sampai akhirnya pada 5 September aku bisa pergi lagi untuk melakukan penjelajahan gunungapi. Pendakian pertamaku di Jawa, ke Gunung Merapi.
Di sela-sela waktuku bekerja, aku hanya bisa sesekali pergi di sekitar kota. Aku berjalan-jalan mengunjungi Keraton dan Tamansari. Istana yang banyak berupa reruntuhan ini mengingatkanku pada reruntuhan Istana Mansfeld di kampung halamanku, tempat aku menghabiskan begitu banyak waktu di masa kecilku. Ada bentuk-bentuk yang menarik perhatianku, juga candi-candi yang aku kunjungi, seperti Prambanan, Kalasan, Candi Sari, Candi Sewu. Aku juga banyak melihat peninggalan-peninggalan Hindu. Batuan-batuan disusun terundak dan membentuk gerbang, batuannya adalah trakhit. Aku mendeskripsi begitu banyak vegetasi, menangkap serangga, mengumpulkan specimen-spesimen sebanyak yang aku bisa.

Pada bulan Mei aku mengambil cuti dan mengajak dua orang pembantuku, yang sudah aku ajari cara menangkap serangga dan mengeringkan tanaman, untuk pergi ke Pegunungan Selatan, menuju gua tempat sarang burung dipanen. Aku ditolong oleh Perdana Menteri-nya Sultan, yang bergelar Raden Adipati, karena dia memberiku surat pengantar untuk diberikan kepada kepala desa – kepala desa. Karena ada surat ini, maka pengalamanku pergi ke Pegunungan Selatan menjadi sangat mudah dan menyenangkan, ini juga mencirikan betapa kekuasaan kolonial telah menembus dalam sampai ke pelosok negeri.
Sesampainya aku di desa, banyak orang yang sudah siap untuk ikut dalam rombongan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang disebut Demang atau Ronggo. Ketika aku masuk ke dalam rumah, tuan rumah menyambutku dengan hangat, sambil membungkuk berulang kali dengan penuh hormat. Pembantu lelaki sibuk menggelar tikar, baik di balai-balai, di gubuk bambu, dan juga di lantai tanah, di depan rumah. Aku duduk di bangku, sementara para penduduk desa duduk bersila di bawahku, sambil menempelkan kedua tangan di depan dadanya, membuat pose sembah, kemudian mengangkatnya ke depan hidungnya, sambil membungkuk. Lalu dia memandang ke depan, menunggu surat dari Sultan untuk dibacakan.
Anggota keluarga lelaki duduk di belakang kepala desa. Sementara itu bocah-bocah memanjat pohon kelapa di halaman. Mereka mencengkeram pohonnya dengan tangan mereka yang kuat, dengan jari-jari mereka ada di antara lekuk-lekuk batang kelapa. Ketika mereka sampai di atas pohon, mereka mengeluarkan golok mereka dari pinggang dan memotong buahnya hingga buah itu jatuh ke bawah. Di bawah orang-orang mengambilnya, membelah bagian atas, kemudian mencongkel bagian yang tipis untuk membuka kelapa itu dengan ujung goloknya yang tajam. Tak lama pelayan dari dapur datang sambil menawarkan kelapa sebagai minuman segar untukku. Kelapa dipegang di atas tangan kanan, sementara tangan kirinya membantu menopang tangan kanan. Aku mengambil kelapa itu dan meninumnya, kepala desa tertawa. Aku merasa minuman itu sangat menyegarkan, seolah-olah aku minum dari mata air yang hidup.
Di desa-desa lain, kedatanganku sudah diumumkan oleh tim pendahulu, maka mereka sudah menyiapkan sambutan. Dari kejauhan terdengar riuh melodi gamelan, membuatku tahu bahwa desa sudah dekat ketika kami masih di hutan. Meja-meja disusun dengan rapi, isinya penuh dengan makanan: nasi, ayam panggang, telur, kopi dan buah-buahan. Kemudian gadis-gadis penari dengan bajunya yang berwarna-warni dan perhiasan yang bergemerincing, mereka sudah siap bergerak seketika perintah diberikan. Ke manapun aku pergi aku selalu ditemani oleh kepala desa, yang berkendara bersamaku dengan kuda. Ia menyiapkan semua jalan untukku. Dari sana aku menjadi tahu tentang keramahan dan kebaikan orang Jawa.

Setelah beberapa hari berkendara naik kuda dan berjalan kaki dari desa ke desa, melewati bukit-bukit yang rapat, dataran, padang alang-alang yang tinggi dan tajam, aku akhirnya tiba di Pantai Selatan Jawa. Samudera Hindia terbentang di hadapanku seolah tak berujung, seperti hamparan mahaluas yang terbentang hingga ke Kutub Selatan. Dari tinggian, daratan menurun perlahan ke arah selatan, tertutupi oleh pohon-pohon Jati muda (Tectonia grandis), yang bunga kecilnya berwangi manis, seolah melembutkan udara. Di antara batang—batang jati terdapat semak rumput yang tinggi, sangat tinggi, hingga seringkali kuda dan penunggangnnya seolah hilang di antara jalan setapak yang seperti bergelombang disapu angin. Jalan setapak ini diketahui juga merupakan jalur jelajah Harimau, yang seringkali bersembunyi memburu mangsa. Tak hanya sekali kuda-kuda mendengus seolah insting bertahan hidupnya merasa terancam.
Di lembah yang sempit terdapat sawah yang hijau, dan di sana pondok-pondok kecil tersebar di antara teras sungai dan tersembunyi di balik semak-semak bambu yang rapat. Terlihat dari tidak adanya pohon kelapa atau kebun pisang, maka bisa diduga bahwa pemukiman ini belum begitu lama didirikan. Menuju malam kami tiba di Dusun Kebo Koening, yang terdiri atas empat buah rumah, yang dibangun di lereng. D sepanjang teras sungai kecil tumbuh semak Cassia alata yang seolah bersinar kehijauan di atas batupasir berwarna putih yang berselang-seling dengan massa batuan volkanik. Aku berusaha untuk mendeskripsi setiap tempat yang aku datangi dengan seksama, sebagaimana seorang pengelana yang melihat sesuatu untuk kali pertama.
Aku bermalam di salah satu pondok dan membakar api unggun yang besar tak jauh dari pondok untuk mengusir nyamuk-nyamuk, dan terutama agar tidak memancing si Raja Hutan, yang menurut penduduk desa seringkali datang mencari mangsa.
Waktu embun pagi masih menggantung di dedaunan, kami sudah melanjutkan perjalanan. Aku senang menemukan jamur, yang di sini hidup tidak tergantung pada musim, apalagi di pegunungan, karena tingginya curah hujan, bahkan saat musim munson timur sekalipun.
Aku melanjutkan perjalanan di pesisir pantai dan perbukitan Gunung Sewu, yang letaknya di sebelah tenggara dari Jogja. Waktu itu aku belum familiar denga bahasa Melayu, sehingga aku menyebutnya sebagai Gunung Sebu. Aku serasa berada di surga.
Puluhan sapi merumput di kaki bukit. Mereka dikalungi lonceng kayu berbentuk kotak di lehernya. Suara gemeretak lonceng mengingatkanku pada melodi hutan di Pegunungan Harz. Aku menduga bahwa lonceng-lonceng ini dipakai untuk menakuti harimau. Belakangan aku tahu bahwa itu keliru, karena di mana-mana di seluruh Jawa kerbau dan sapi dipasangi lonceng, bahkan di tempat yang tak ada harimau sekalipun. Tujuan dari lonceng ini adalah untuk si penggembala, agar dia tahu di mana gembalanya berada. Seringkali si penggembala ini main-main mencari jangkrik, atau ketiduran, sehingga kehilangan jejak hewan gembalaannya.
Oh betapa aku ingin menggambarkan keindahan perbukitan sunyi dan sepi, yang ada di tempat terpencil di bumi. Ketika itu keindahannya tak berbanding. Tentu saja, ini adalah perjalanan berwisataku yang pertama. Aku belum melihat begitu banyak tempat indah lain di Jawa seperti Ijen atau Priangan. Tapi Gunung Sewu adalah pemandangan yang menakjubkan. Ada ratusan atau ribuan bukit, yang tingginya seratus hingga dua ratus kaki. Bukit-bukit ini terpisah oleh lembah-lembah sempit yang seperti labirin. Bukit-bukit ini serupa satu sama lain, seluruhnya diselimuti hutan yang rapat oleh berbagai macam tanaman. Pada lembah-lembah yang cukup lebar, hutan akasia seolah memamerkan tajuknya yang renggang, membuatku seperti menatap birunya langit dari anyaman yang halus. Di hutan yang begitu padat, daun pisang yang lebar dan datar seolah bersinar. Keheningan yang syahdu kadang dipecahkan oleh kikuk burung merpati atau kokok ayam hutan. Itulah yang aku rasakan ketika menerobos Gunung Sewu untuk menuju gua sarang burung di Rangkop, pantai di tepi Samudera Hindia.
Tak jauh dari pantai terdapat rawa-rawa kecil, di sana capung dan bermacam-macam serangga berbunyi nyaring pada rawa yang berlumpur. Tak jauh terdapat sebuah lubang besar antara dua dinding yang terjal. Bagian atas penuh diselimuti semak, yang menggantung seperti mau jatuh. Di bawahnya terdapat celah sempit yang mengerikan. Orang lokal menyebutnya sebagai Liang dan aku menuruninya dan tiba di satu dataran kecil yang dikepung oleh perbukitan dan memandang ke arah lautan tak berbatas, dengan sedikit terhalang pohon-pohon palem yang sangat rapat.
Ada satu rumah kayu di sana. Rumah itu kosong tak berpenghuni, setidaknya penghuni yang hidup. Menurut warga, penghuninya adalah Nyai Rangkop, roh gaib yang berkuasa atas Gua Rangkop. Pada malam hari dia konon suka bertetirah di sini, sesuka hatinya. Rumah ini dirawat oleh warga lokal. Ada balai untuk Nyai Rangkop duduk, ada sarung dan kebaya digantung di dinding untuk dipersembahkan kepadanya. Aku berjalan melewati rumah ini dan sampai di ujung dari Batu Rangkop, tebing batu tegak yang dalamnya mencapai 80 kaki hingga permukaan laut. Di bawahnya deburan ombak terlihat kentara, meskipun dasar batuannya tak tampak karena bagian bawahnya menjorok ke dalam. Di seberangnya ada batuan berwarna abu kehitaman yang hancur-hancur diselimuti semak, yang seperti karpet. Di antara celh, orang Jawa melintangkan kayu, yang kemudian ke kayu itu dikaitkan tangga bambu yang disambungkan dengan rotan. Tangga ini menggantung 30 kaki di atas permukaan laut. Orang Jawa menuruni tangga ini untuk mencapai Gua Rangkop, yang di sana terdapat sarang burung yang bisa dimakan.
Aku bertemu dengan seorang Belanda yang sudah tua. Dia tinggal di desa ini dan menjadi satu-satunya orang Eropa di antara mereka. Dia bertanggung jawab untuk mensupervisi pemanenan sarang burung. Orang ini memanggil pemanen dan menyuruh mereka untuk menunjukkan cara memanen kepada tamu yang datang ke sana, apalagi yang mendapat rekomendasi dari Sultan Yogya. Aku dan rombonganku duduk di tepi tebing di sisi timur Rangkop, di mana aku bisa melihat gua tempat sarang burung ini dengan begitu jelas. Pintu masuk gua itu ada 20 kaki di atas permukaan laut. Pada ketinggian itu ada anyaman rotan yang berfungsi sebagai pijakan. Pemanen sarang menginjak pinjakan di dinding Rangkop dan dengan perlahan menuruni tangga. Mereka berhenti sekali-sekali tapi tidak lama. Mereka juga menunggu saat yang tepat untuk bisa masuk ke dalam gua, karena ombak terus bergemuruh. Ombak datang menghantam dan masuk ke dalam gua, bergemuruh seperti petir. Beberapa saat berlalu, akhirnya ombak mundur cukup jauh ke laut dan warna merah bebatuan kini tersingkap lagi, hingga kmudian ombak menghantam lagi dengan suara yang nyaring, juga dengan uap yang memenuhi udara seperti asap.
Ratusan burung wallet juga bergerak mengikuti irama ombak. Mereka masuk dan keluar seolah-olah mengikuti saat ombak mengizinkan mereka. Setelah duduk di anyaman sekian lama, orang Jawa mengikat tali rotan di pinggang kawannya. Orang yang diikat kemudian meloncat ke laut dan berenang menuju gua di saat ombak tinggi. Tak lama kemudian ketika ombak mereda ia Kembali. Penjaga bilang bahwa sebelum musim panen di Januari, Mei, dan Agustus, oran yang sama masuk ke dalam gua, juga dengan cara yang sama, dan kemudan memperbaiki anyaman rotan di dalam gua. Merayap di tali rotan, teman-temannya datang membawakannya tangga, yang akan dipasang sepanjang 70 kaki ke dalam gua hingga mereka bisa sampai di sarang wallet. Sebelum mereka bekerja, mereka minum candu, agar mereka jadi berani dan tidak meragu.
Amarah lautan dan gemuruh di gua adalah ulah Nyai Rangkop. Untuk itu maka sesajian diberikan untuk menghormati Nyai Rongkop. Sebagian di rumahnya, sebagian lagi di ujung batas jurang. Seorang tetua akan berlutut di dekat meja persembahan sambil berteriak, „roh telah tiba!” Mereka kemudian duduk dengan kepala menunduk sampai si tetua mengizinkan mereka untuk menegakkan kepala. Ketika selesai, maka mereka dipersilakan untuk memakan sesajian. Makanannya tidak berkurang secara jumlah, tapi rasanyan hilang, karena arwah gaib telah menyerap seluruh saripati dari makanan tersebut. Roh itu sangat dihormati di seluruh desa, bahkan pada pesta pernikahan, tarian pertama para penari harus dipersembahkan kepada Nyai Rangkop.